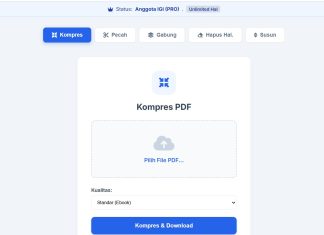PENDIDIKAN HARUSNYA MONDOK
Oleh: Khairuddin
(Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat IGI)
Mondok di Indonesia identik dengan pesantren atau dayah dalam istilah populer di Aceh. Wajar saja karena pola pendidikan mondok memang digagas oleh pesantren. Belakangan tren mondok mulai bergeser, sekolah-sekolah umum atau madrasah yang berlabel “unggul” atau sekolah yayasan serta sekolah semi militer mulai mengasramakan siswa bahkan gurunya untuk suatu pola pendidikan terintegrasi dengan nilai-nilai visi misinya. Uniknya, pesantren-pesantren juga bertransformasi mengelola pendidikan yang memadukan ajaran agama dengan pendidikan umum formal.
Dayah terpadu di Aceh memiliki kurikulum ganda, pagi hingga siang menyelenggarakan pendidikan umum formal mengikuti kurikulum nasional, sore diisi oleh pembinaan fisik dan mental, sementara malam diisi oleh pengajian salafi khas kitab kuning, bahasan mendetil tentang fiqh, tauhid, tasawuf, akhlak, adab, tata bahasa arab serta tafsir Al-Qur’an dan kecakapan verbal melalui muhadharah. Mulai pendidikan pada jam 7.30 hingga 22.00 WIB. Dayah terpadu mengacu pada kelulusan nasional, tetap saja mengikuti UN lazimnya sekolah umum lainnya. Pola yang sama saya pikir dengan sekolah umum yang mondok, paginya kurikulum nasional sementara malam hari penekanan pada kegiatan siswa pengembangan bakat atau kecakapan life skill.
Meski demikian di Aceh masih sangat banyak Dayah Salafi Murni tanpa mencampuradukkan dengan kurikulum nasional, tetap saja mondok. Pengajian dimulai jam 6.30 hingga 23.00. Ujian kenaikan kelas juga dilaksanakan, namun naik kelas bukan hanya karena pengetahuan tapi juga berdasarkan kesadaran, semisal seorang santri merasa belum pantas naik kelas karena masih haus kajian ilmu, meski nilainya tinggi boleh saja meminta untuk duduk di kelas lama. Tidak ada ijazah, tidak ada SPP bulanan, nyantri aja dengan ikhlas dan biaya murah. Lapar kenyang, sedih bahagia, ya jamaah saja, nangisnya bisa bareng. Jangan dikira dayah seperti ini miskin peminat, banyak di Aceh yang harus menambah bilik2 asrama karena kedatangan calon santri dari luar daerah, bahkan banyak dari luar aceh seperti Sumbar, Jambi, Lampung, Sumsel. Mereka yang datang dari luar Aceh, lazimnya tak pulang kampung jika ilmunya masih minim, minimal cakap khutbah Jumat atau menjadi imam serta mendirikan dayah baru di kampung halamannya. Orangtua mereka sepertinya sudah ikhlas menyerahkan hidup anaknya pada pimpinan dayah bertahun-tahun lamanya tak pulang2. Bahkan ada yang dari usia kelas 1 SD sudah dititip pada pimpinan dayah. Fortunately, pimpinan dayah menerima ikhlas dititip tanpa kiriman bulanan, menanggung hidup seperti anak kandungnya.
Tercatat hanya dua di Aceh, dayah salafi yang mulai mengelola pendidikan ganda tapi lebih mengutamakan pada kecakapan ilmu-ilmu agama, salahsatu dayah tersebut adalah Pesantren Babussalam Matangkuli yang dekat dengan rumah saya. Pola pendidikannya dinamai Pendidikan Diniyah Filial (PDF), mengelola pendidikan pada level SMP dan SMA. Ujian nasionalnya kurikulum kitab kuning, berijazah dengan ilmu agama yang mumpuni. Bahkan dengan diresmikan Ma’had ‘Ali di pesantren ini untuk mengelola pendidikan tingkat tinggi, saya semakin yakin lulusan-lulusan ini akan mampu memurnikan ajaran Islam di Aceh di tengah era bebasnya informasi. Mereka layak berkontribusi di kantor pemerintahan yang berafiliasi dengan Kementerian Agama, termasuk menjadi guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum.
Di tengah isu zonasi pendidikan yang sebagian pro dan kontra, Dayah menjadi pilihan yang semakin diminati. Hampir tidak ada korelasi zonasi dengan minat orangtua menyerahkan anaknya ke dayah. Terlebih dayah, madrasah, sekolah vokasi yang diakui pemerintah tidak terkait aturan zonasi, bahkan sekolah vokasi tidak pusing memikirkan kewajiban pemenuhan jumlah siswa per kelas. Ketertarikan orangtua lebih pada “mondok” yang memberi dampak positif di tengah gencarnya bahaya gawai di era disrupsi yang tidak mampu digunakan secara sehat oleh remaja milenial, sementara orangtua rabun teknologi. Anak yang mondok meski miskin kompetensi sosial, namun berakhlak lebih baik, lebih santun, lebih teratur serta lebih disiplin beribadah dan cakap mengelola waktu.
Karena itu, sebagian orangtua yang memiliki pendapatan menengah ke atas memilih sekolah mondok yang menjanjikan pembinaan karakter meski harus membayar mahal, sementara banyak orangtua yang ekonominya menengah ke bawah memilih dayah murni. Meski saya tak mengeneralisir, orang miskin ke dayah murni, karena ternyata dalam mengejar ilmu agama yang kokoh banyak orangtua kaya raya memilih pendidikan anaknya di dayah murni. Intinya, banyak hal positif yang dirasa orangtua memperbaiki akhlak karakter anaknya melalui pendidikan bermondok, meski harus pontang-panting cari uang tambahan demi anaknya. Tak terkecuali anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah umum, yayasan, semi militer yang berasrama, pilihannya pembinaan karakter selain skill menjadi yang utama. Orangtua khawatir dengan bebasnya dampak negatif di gawai.
Ini kritikan bagi pendidikan umum tanpa mondok, selain belum menunjukkan identitas pembinaan karakter yang berhasil juga prestasi akademik yang kerap kalah dengan sekolah berasrama. Pengelola pendidikan daerah harus memformulasi, jika tidak mondok, sekolah umum harus punya kekhasan yang membuat masyarakat punya pilihan pendidikan yang baik bagi anaknya. Banyak sekolah di kampung yang masih diminati oleh masyarakat selain karena daripada menganggur, jam sekolahnya lebih pendek sehingga bisa membantu orangtuanya, serta masih bisa dijangkau bahkan memberi “uang masuk” bagi siswanya. Pilihan seperti itu pun tidak salah, namun layanan pendidikan tetap harus optimal sehingga tidak membuat kesenjangan kualitas yang seolah-olah sekolah beginian boleh seadanya saja. Setiap sekolah harus mencirikan sesuatu sebagai output unggulan bagi siswanya dan pemerintah memfasilitasi itu melalui penyediaan guru-guru unggul di sekolah dengan distribusi merata.
Konon dulu, kalau ada guru bermasalah pasti diancam dibuang ke daerah terpencil, pelosok, wajar saja banyak guru berusaha eksodus ke daerah perkotaan, selain mudah mengelola pendidikan juga menghindari image buruk sebagai guru bermasalah. Pemerataan kualitas pendidikan bukan tanggungjawab guru semata sebagai agen pemerintah, tapi juga political will dari pengambil kebijakan daerah. Benahi pendidikan tanggungjawab bersama, pemerintah, instansi dan masyarakat sekitar.
Zonasi pendidikan bagus menurut saya, meski harus sabar menanti dampak baiknya. Namun yang lebih penting benahi lembaga pendidikan bagi guru, benahi rekrutmen guru, perbaiki kualitas guru, lalu distribusikan guru secara merata. Jika perlu zonasi gurunya karena kualitas merata, jadi meski tidak mondok, karena semua terjangkau, sekolah umum bisa serasa mondok, tinggal ajak orangtua dan masyarakat merasa memiliki pendidikan. Orangtua pasti tidak khawatir jika anak pulang larut dari sekolah, dekat mudah dipantau, guru pun tidak keberatan menambah waktunya hingga larut di sekolah, sepanjang seluruh khauri di gampong sudah disaweue.